.jpg)
Through love and acceptance, we feel we belong. Through what this world offers, happiness found. It takes a whole life to seek for that. In the end, it doesn't bring anything at all. - Hope (SYC 2018)
Apa yang terbesit di benakmu saat hujan tiba?
Banyak orang menghubungkan hujan dengan kenangan di masa lalu, terutama dengan orang yang (pernah) menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Teman-temanku juga mengatakan hal yang sama, bahkan ada yang bilang, "Bagus sih, kalau sampai sekarang kita masih bersamanya; karena saat hujan turun, kita ingin merasakan momen romantis bersamanya. Tapi kalau udah putus, aku sendiri malah jadi benci musim hujan. Soalnya setiap tetes air di dalamnya bisa mengingatkanku pada setiap peristiwa yang pernah kami lalui."
Aku bukan tipe orang yang suka merenung saat hujan. Buatku, lebih baik tidur saja karena hawanya bobok-able. Tapi setelah memasuki tahun yang baru, entah kenapa akhir-akhir ini aku jadi memikirkan sesuatu yang mengganjal di pikiranku... apalagi saat hujan tiba. Pikiran itu membawaku pada dua peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, sehingga aku menduga bahwa semua hal itu saling berkaitan.
---
Beberapa hari sebelum pulang untuk liburan, aku sempat makan malam dengan tiga teman kuliah di sebuah kafe di dekat kampus. Dua di antara kami tidak pulang karena harga tiket pesawat yang melangit, sementara aku dan temanku yang lain akan pulang besok pagi. Kami mengobrol tentang keunikan tempat asal masing-masing, dan juga soal relasi kami dengan yang-nun-jauh-di-sana. Yeah, bukan kebetulan kalau kami berempat sudah memiliki pasangan; bersama mereka, aku benar-benar sadar bahwa LDR itu penuh tantangan. Obrolan kami semakin seru (terutama karena aku sedang membicarakan kota asalku), sampai tiba-tiba Christo bertanya, "Emang kamu mau balik ke mana, Ta?"
Tanpa pikir panjang, aku menjawab, "Pulang kepada siapa saja yang menerimaku."

Awalnya aku hanya menganggap itu jawaban biasa, sampai tibalah hari dimana aku meragukan relasiku dengan Kak Peter. Hari itu adalah hari ini, 7 Januari yang diisi dengan guyuran hujan di mana-mana.
---
Kak Peter bukan cowok biasa, gengs. Dia termasuk orang yang istimewa, bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga karena dia menderita asma sejak kecil. Dampaknya jelas: cowok yang empat tahun lebih tua dariku itu jadi sangat anti terhadap hawa dingin—padahal aku justru sebaliknya. Pernah ada kejadian dimana kami (bersama beberapa teman lainnya) pergi berkemah di Kaliurang, tapi tiba-tiba asmanya kumat sehingga kami harus pulang duluan. Sejak saat itu Kak Peter kapok kemping, bahkan untuk ke mall pun dia hanya bisa bertahan maksimal tiga jam saking tidak tahannya dia terhadap hawa dingin. Emang sih, dia cowok yang baik... terlalu baik buatku yang sangat sulit untuk menerima diri sendiri—apalagi dirinya yang sakit-sakitan seperti itu!
Ditambah lagi, sejak aku berada jauh darinya, aku merasa ada beberapa teman cowok yang (mencoba) mendekatiku. Karena sadar akan bahaya LDR, aku menceritakan tentang relasi kami pada mereka. Tidak sedikit yang mulai menjaga jarak dariku (meskipun kami masih tetap berteman), tapi ada satu-dua orang yang tetap bersikukuh mendekatiku. Ada yang bilang, “Selama janur kuning belum melengkung, masih ada kesempatan untuk menikung.” (Haha… bercanda, kok). Akibatnya, aku jadi menyadari kalau ada cowok yang kondisi fisiknya lebih baik daripada Kak Peter dan dia memperhatikanku.
Christo adalah salah satunya. Cowok yang dua tahun lebih tua dariku itu cukup sering mengajakku mengobrol, terutama saat aku sedang sendirian (mungkin karena dia kasihan sama aku haha). Banyak yang bilang kalau Christo termasuk cowok yang “langka”, bukan karena dia aneh atau semacamnya, tapi karena keramahannya yang menghangatkan—sesuatu yang tidak biasa ditemukan di kota metropolitan seperti di sini. Dia juga merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dan pengurus organisasi di kampus. Oh, satu lagi: Christo juga jarang sakit, satu nilai plus darinya kan?
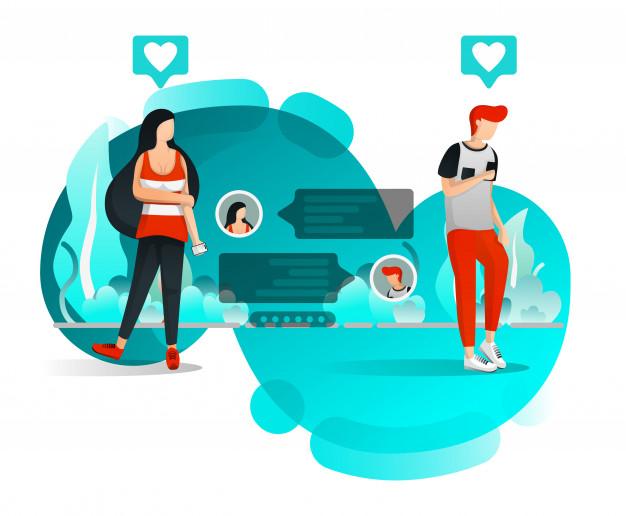
Itulah kenapa aku mulai ragu pada relasiku sendiri. Aku menyalahkan diriku yang terlalu tergiur pada cinta yang ditawarkan Kak Peter tiga tahun yang lalu, sehingga tidak melihat ada kemungkinan terburuk yang bisa menimpanya. Well, diriku tiga tahun yang lalu tentu tidak berpikir bahwa aku yang sekarang akan berteman dengan banyak cowok yang lebih sehat dan sefrekuensi denganku—kalau dibandingkan dengan Kak Peter. Ditambah lagi, satu-dua di antaranya adalah orang yang seperti itu. It’s so funny, right?
PING! PING! PING!
Aku menatap layar handphone-ku dan melihat pemberitahuan bahwa Kak Peter mengajakku video-call. Oh, pasti mau bahas chat-ku tadi sore, pikirku, lalu mengangkat telepon.
Sejujurnya, momen ini adalah momen paling menjemukan dalam relasi kami. Well, aku bisa memahami kalau Kak Peter marah padaku karena aku terlihat tidak ingin memperjuangkan relasi ini lebih lanjut. Aku juga maklum kalau dia memakiku yang masih suka mengungkit masalah-masalah di masa lalu, dan menuntutnya—sementara dia malah tidak balas menuntut.
Di luar dugaan, Kak Peter berkata, “Aku nggak marah, kok.”
Aku menautkan alis. Nggak marah? Setelah semua tuntutan dan tuduhan yang kuberikan padanya itu? batinku tidak habis pikir.
“Aku nggak akan nuntut kamu, Ta. Terserah kamu mau gimanain relasi kita ini. Tapi seenggaknya, coba pikir lagi apa kamu bener-bener mau berhenti berjuang bersamaku—yang udah bersedia menerimamu apa adanya… termasuk sifat perfeksionismu.”
Meskipun aku berusaha untuk bersikap dingin padanya, tetap saja perkataannya itu melelehkan perasaanku yang membeku. Dengan senyuman kecil, dia melanjutkan, “Aku paham kalau kamu masih sulit menerimaku yang sakit-sakitan ini. Jadi pilihan berikutnya ada di tanganmu, entah kamu mau tetap melanjutkan perjalanan ini bersamaku atau nggak.”
Duh, ini cowok gampang banget bikin aku nangis, sih, pikirku saat menyadari ada genangan air di mataku. Akhirnya aku mengakhiri telepon itu dan berkata, “Ya udah. Seenggaknya sekarang kamu tahu kalau aku udah mikirin kemungkinan terburuk dari relasi ini. Aku tutup teleponnya, ya.”
Setelah menutup telepon, aku membenamkan kepala ke bantal dan menangis keras. Please, deh, aku semakin bingung dengan keputusan yang harus kuambil. Secara teori, aku tahu kalau aku nggak bisa menjalin relasi berdasarkan rasa kasihan dan rasa bersalah. Tapi di sisi lain, aku juga takut kalau nggak bisa menemukan cowok yang—bukan cuma sehat—sebaik dan sesabar Kak Peter padaku.
Ditambah lagi, aku teringat pada momen makan malam beberapa minggu lalu, tepatnya setelah aku curhat panjang-lebar pada Winona, Christo, dan Hansel. Kedua cowok itu manggut-manggut saat Winona menepuk-nepuk bahuku dan berkata, “Yah… selalu ada konsekuensi dalam setiap pilihan yang kita ambil ya, Ta. Di satu sisi, kita pasti nggak pengen putus kalau punya pasangan sebaik Kak Peter. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengakui ada kemungkinan terburuk yang bisa menimpanya yang mudah sakit… tinggal kitanya yang siap apa nggak.”
Jujur saja, aku paling tidak suka berada di posisi serbasalah seperti ini. Memang sih, rasanya akan lebih mudah bagiku kalau aku menghentikan langkahku di sini; tapi bagaimana dengan Kak Peter? Relasi ini adalah relasi pertama bagi kami, dan aku tidak ingin merusak anggapannya bahwa dirinya layak untuk dicintai. Tidak. Aku sendiri juga merasa tidak sanggup mencintainya dari diriku sendiri… apalagi menerima cintanya yang tulus dan kesabaran ekstranya itu.
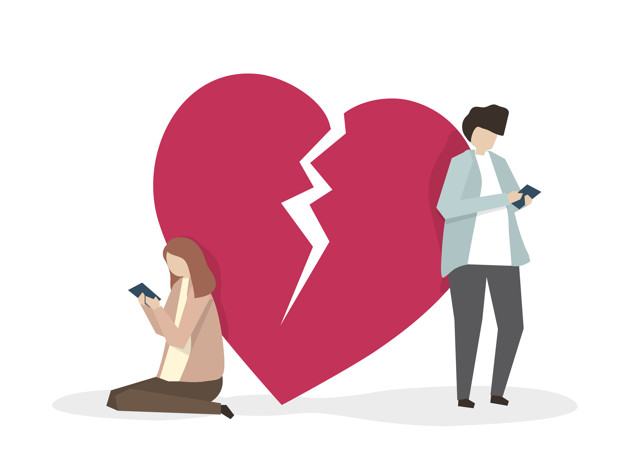
TOK! TOK! TOK!
Aku mengusap mataku, lalu beranjak dari kasur untuk membuka pintu. Di depanku ada Winona yang tersenyum. “Ada yang kasih ini, nih,” katanya sambil menyodorkan sekotak coklat dan kertas yang diselipkan di bawah pita biru muda.
“Eh… makasih, Win,” balasku. “Tahu aja aku baru butuh coklat sekarang.”
Dia tertawa. “Ini bukan dari aku, kok. Ada yang titip, katanya dia malu kalau ngasih langsung.”
Aku mengerutkan dahi. “Cowok, ya?” tebakku.
Bukannya menjawab, Winona malah nyengir. “Mungkin jawabannya ada di kertas itu,” jawabnya.
Setelah Winona pergi, aku menutup pintu dan membuka kertas itu. Ternyata isinya surat, yang sukses membuatku menangis. Bukan karena itu dari Peter, tapi justru dari seseorang yang tidak pernah aku duga akan memberiku semangat semanis ini. Yah… aku bersyukur karena aku nggak berjuang sendirian; ada orang-orang yang berkenan menyediakan hati dan telinganya untuk menguatkanku… sebagai bukti bahwa Tuhan tetap mengasihiku—bahkan saat aku tidak memahami jalan pikir-Nya.
Dear Christabelle,
Ga mudah ya, kalo orang yang kita kasihi ternyata menderita penyakit yang sulit untuk sembuh. Dua minggu lalu, waktu kita makan bareng Hansel sama Winona, aku nggak nyangka kalo kamu bakal cerita banyak soal pergumulanmu itu. Maaf aku nggak berani banyak ngomong karena aku juga ngerasain apa yang kamu rasain. Pacarku baru sakit leukemia, dan waktu kamu baca surat ini, aku udah balik ke Balikpapan karena kondisinya udah tambah kritis. Apa yang Winona bilang bener. Tinggal kita siap apa nggak buat menghadapi kemungkinan terburuk itu. Dan… itu nggak mudah.
Inget nggak, abis itu Hansel bilang, “Apapun keputusanmu, tetep belajar buat memuliakan Tuhan, ya”? Itu nusuk banget, karena yah… kadang-kadang aku juga nyalahin Tuhan yang tega kasih penyakit parah ke pacarku. Padahal dia juga sabar banget, sama kayak pacarmu yang mau menerima dan mencintaimu tanpa banyak menuntut. Sampai sekarang aku nggak ngerti apa yang Dia mau dari kami. Kalau pacarku emang harus "pergi", kenapa Dia nggak berhentiin hubungan ini jauh sebelum kami melangkah lebih jauh? Mungkin itu juga yang kamu dan pacarmu rasain ya, Ta?
Tapi nggak apa-apa. Mungkin dari ketidakmengertian kita, Tuhan pengen kita lebih percaya sama Dia—bahkan saat keadaannya membuat kita ragu-ragu untuk melangkah dalam rencana-Nya. Kita bisa aja jadi orang yang perfeksionis, tapi toh tetep rapuh. Ya, kan? Justru kita yang nggak sempurna di hadapan-Nya dilayakkan-Nya untuk terlibat dalam karya-Nya yang sempurna, walaupun sekarang kita nggak bisa lihat akhir dari perjalanan kita.
Semangat, ya.
Yang memandangmu dari jauh, tapi memelukmu di dalam doa.
Untuk menjadi bagian dari gerakan generasi
muda Kristen Indonesia. Kirimkan karyamu ke: