
Karena setiap kehidupan itu berharga, maka hidupilah hidupmu dan cintailah cintamu.
Cokelat kekuningan, berlapis keju, lengkap dengan taburan serbuk daun oregano dan potongan sosis. Namanya Roti Ragi. Meskipun sudah terbungkus di dalam kardus makanan yang kujinjing menggunakan tas kanvas, aromanya tetap saja memikat rambut hidungku. Menggoda lambungku. Menjerat air liurku.
Aku mendapatkan roti ini dari teman kantor yang sedang berulang tahun. Beberapa dari kami langsung melahap roti itu saat istirahat siang tadi. Awalnya, aku juga tak sabar ingin mencicipi kelezatanya. Hanya saja, aku memilih untuk memakannya nanti. Di rumah. Alasannya, tidak lain karena aku tiba-tiba saja teringat akan suamiku. Seseorang yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain—terlebih kepada istrinya—dari pada dirinya sendiri. Di samping itu, jenis roti yang demikian merupakan salah satu makanan favorit kami.
Aku teringat ketika suatu pagi, kami sarapan dengan roti lapis daging yang dipanggang. Tanpa sengaja, aku memanggang roti terlalu lama hingga sedikit gosong. Pikirku, akulah yang seharusnya memakan potongan yang menghitam itu. Namun, pikiran suamiku ternyata berbeda. Ia memilih untuk mengambil potongan yang pahit itu, bahkan ia masih mengucapkan terima kasih.
***
Bicara soal “terima kasih”, ungkapan sederhana seperti itu sangatlah berarti bagiku. Terlebih ketika perkataan itu diucapkan setelah ia memakan roti gosong buatanku. Rangkaian dua kata tersebut mampu membuat hati ini bergetar. Ditambah lagi, ia mengatakannya sambil tersenyum. Bukan senyuman sinis untuk menyindir ataupun mengejek, tetapi sungguh-sungguh senyuman yang dilandasi dengan perasaan syukur. Sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kudengar darinya usai menikmati hidangan yang kelezatannya diragukan.
Lain pula ketika aku harus belanja di supermarket. Biasanya, para pria akan mengeluarkan ribuan alasan untuk tidak mendampingi istri-istri mereka berbelanja. Atau jika terpaksa harus mengantar, mereka memilih untuk memisahkan diri dan duduk bersantai sembari meneguk secangkir kopi. Membiarkan pasangannya berkeliling menyusuri rak-rak sendirian. Baiknya, suamiku itu tidak termasuk jenis yang demikian.
Tanpa harus memohon, dengan senang hati ia akan mengantarku berbelanja. Berjalan di sampingku sambil memilah barang-barang keperluan rumah tangga. Jika ia sedang memiliki kesibukan lain yang tidak dapat ditunda, ia akan memintaku untuk menunggunya. Atau ia akan menawarkan hari lain agar kami dapat berbelanja bersama. Dan aku pun tidak pernah merasa keberatan jika harus menunggu. Karena aku tahu, ia pasti akan menepati janjinya. Sungguh menyenangkan, bukan?
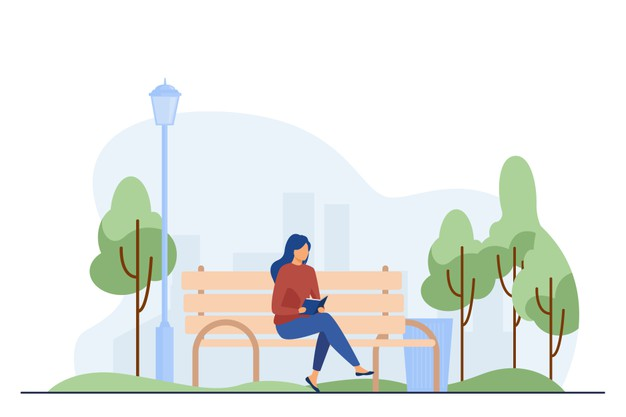
Petang ini, aku bagaikan seorang hakim yang harus memutuskan persoalan hidup dan mati. Di satu sisi, aku ingin berbuat sesuatu untuk suamiku. Sesuatu yang sederhana, tetapi mampu membuat senyumnya merekah. Dan kebetulan sekali, hari ini aku pulang membawa Roti Ragi. Aku ingin mengulang waktu kebersamaan kami dengan memakan kudapan itu berdua dengannya.
Di sisi yang lain, tidak dapat dipungkiri lagi jika sejujurnya aku benar-benar ingin melumat roti itu. Jika tadi siang aku dapat menahan untuk tidak memakannya, itu karena perutku sudah terisi bekal nasi yang kubawa. Sayangnya, saat ini, naga dalam perutku mulai menggeliat. Apalagi roti yang masih kujinjing ini seolah melambai-lambai dan menjanjikan kelezatan. Namun, mengingat bahwa seorang hakim haruslah bijaksana, maka….
Aku memejamkan mataku. Menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiranku. Mencoba mengosongkan pikiranku dari segala bentuk hasutan iblis yang akan mempengaruhi keputusanku.
Jika suamiku saja sanggup memberikan hari-hari terbaiknya untuk kami berdua, sudah seharusnya aku pun dapat melakukan hal yang sama. Bukan besok, ataupun besok-besok, tetapi hari ini. Entah mengapa, aku tidak ingin menundanya. Terlebih aku sudah mempersiapkan hal ini sedari siang. Sungguh memalukan bila rencanaku selama beberapa jam ini pupus begitu saja lantaran urusan perut. Tidak. Hal itu tidak boleh terjadi.
Pphhhhhssss….
Pintu bus yang kutumpangi tiba-tiba saja terbuka.
Ya Tuhan, entah karena aroma roti ataukah suami yang menghipnotis pikiranku. Yang pasti, aku bahkan tidak menyadari bahwa bus yang mengantarku pulang sedang merapat di halte. Dua orang wanita yang tadi sempat kulihat sedang duduk di ujung ketika aku masuk, sekonyong-konyong sudah berdiri di dekatku. Mereka hendak keluar dari bus. Sontak aku mengangkat jinjingan tas lebih tinggi agar roti yang kubawa tidak tersenggol oleh mereka.

Tak berselang lama, aku melihat ada kursi-kursi yang kini telah kosong. Tanpa berpikir panjang, aku menghampiri kursi itu dan duduk di atasnya.
Setelah hampir satu jam berdiri di dalam bus, akhirnya aku dapat melepaskan kelelahanku. Meluruskan kaki sekaligus menyandarkan punggungku. Roti yang sejak tadi kujinjing, kini berada dalam pangkuanku. Lebih aman, dan akan tetap aman hingga kami dapat menikmatinya berdua. Sekali lagi aku menarik napas dalam-dalam serta bersyukur sekaligus menyadari bahwa… meskipun sudah dalam keadaan duduk, pergumulanku ternyata tidak sepenuhnya selesai.
Rupanya, memangku roti justru semakin menggelitik indra-indraku. Mataku dapat memandangnya lebih jelas. Hidungku semakin mencium aromanya dengan baik. Tanganku semakin mudah untuk membuka bungkusannya lalu mengantarkan sepotong kecil roti ke mulutku.
Ah, ada-ada saja aku ini. Aku menggelengkan kepalaku beberapa kali untuk membuyarkan godaan tersebut. Sempat terpikir olehku untuk berdiri saja sehingga terhindar dari pikiran-pikiran nakal untuk mencuil roti. Sayangnya, aku merasakan tubuhku sedang tidak bersahabat. Mungkin saja aku terlalu lelah karena seharian bekerja. Belum lagi, sejak tadi aku sudah berdiri cukup lama di dalam bus. Atau… bisa jadi, malam ini adalah ujian untukku.
Baiklah, kembali ke rencana semula. Keinginanku adalah menikmati roti ini bersama dengan suamiku. Walau hanya dengan sebungkus roti, aku yakin, momen seperti ini akan membekas dalam hatinya. Sekali lalu, aku menengadahkan wajah ke langit-langit bus. Aku memikirkan cara termanis untuk memberikan bingkisan ini padanya. Satu menit, dua menit, dan akhirnya kutemukan cara terindah untuk membuatnya tersenyum malam ini.
Aku mengaduk-aduk isi tas. Mencari beberapa perlatan yang kubutuhkan untuk menjalankan rencanaku. Tidak perlu membuang banyak tenaga, aku hanya cukup menunggu bus berhenti di lampu merah berikutnya. Setelah sopir bus menginjak remnya, dengan cepat aku memindahkan isi kepalaku ke media lain. Dan, persiapanku selesai. Sempurna. Aku tersenyum dalam hati karena rancangan singkatku ini begitu memuaskan. Tinggal menunggu waktunya saja.
Aku melirik ke arah jam tangan yang kupakai. Sebentar lagi, aku akan bertemu dengan suamiku. Ingin rasanya segera melihat senyumnya dan merasakan kehangatan dalam pelukannya. Ingin rasanya untuk mendengar sekali lagi ucapan terima kasih walau sebetulnya kata-kata itu sudah tidak asing lagi di telingaku. Tak heran jika angan-angan tersebut membuatku bersemangat. Membuat jantungku yang sudah berdebar-debar semakin berdetak tanpa irama. Membuat napasku tersekat. Ah sudahlah… tinggal beberapa menit lagi, lebih baik aku duduk diam dan bersabar.
Seraya melipat tangan di atas perut, aku memejamkan mata dan mendapati wajahku tersenyum melihat suamiku. Ia meraih tubuhku. Memelukku dengan erat hingga aku dapat merasakan kekuatan lengannya. Kehangatan tubuhnya. Namun, ketika aku mengangkat wajahku, yang kulihat hanya sepasang mata yang mulai berkaca-kaca.
Ada apa dengannya? Pertanyan itu tidak terucap olehku. Hanya terlintas begitu saja dalam benakku lalu tertahan di tenggorokanku. Lambat laun, aku tidak lagi merasakan kekuatan lengannya. Kehangatannya pun memudar. Bibirnya tidak lagi membentuk senyuman. Akhirnya, aku menyadari bahwa angin telah menarik tubuhku. Memisahkan kami berdua. Dari kejauhan, aku hanya dapat melihatnya tertunduk dalam lingkaran abu.
Meninggalkan semua kenangan.
Membuat hatiku tersayat-sayat.
Begitu menyedihkan.
Sangat menyakitkan.
***

Kira-kira jam sembilan malam, seorang pria mendatangi rumah sakit. Dari tempat parkir, ia berlari sekencang-kencangnya menuju Instalasi Gawat Darurat. Setibanya di sana, ia langsung melihat ke arah sebuah tempat tidur di mana seseorang terbaring dan sudah tertutup oleh kain putih. Di dekatnya berdiri seorang perawat yang sedang membereskan selang-selang yang sepertinya baru saja digunakan.
Sementara pria itu mendekat ke arah tempat tidur, sang perawat menyadari kehadirannya lalu menghentikan pekerjaannya sejenak. Perawat itu, menanyakan identitas pria yang baru saja datang. Ia mengangguk setelah mendapat jawaban, seraya mengambil sesuatu dari dalam laci. Disertai dengan seulas senyum empati, ia menyerahkan sebuah tas berbahan kanvas kepada pria tersebut.
Sambil tertunduk pria itu menerimanya. Menarik ikatan tas, lalu ia menemukan sebuah kertas yang terlipat sedemikian rupa di atas sebuah kardus Roti Ragi. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka lipatan kertas itu kemudian membacanya:
“Sepotong roti tak kan pernah mekar sempurna tanpa ragi, seperti halnya diriku tak kan pernah rekah ‘menjadi seseorang’ tanpamu. Terima kasih sudah mencintaiku.”
Untuk menjadi bagian dari gerakan generasi
muda Kristen Indonesia. Kirimkan karyamu ke: