
“Kalau kehadiran pacarmu itu menggantikan posisi Allah, Allah bakal mengorkestrasi, bagaimanapun caranya, untuk membawamu kembali pada-Nya.” – Seorang dosen
Dulu saat masih bersekolah, aku sering iri melihat teman-temanku yang telah memiliki pasangan masing-masing. Apalagi kalau melihat mereka bisa ngobrol akrab di jam istirahat. Belum lagi kalau melihat foto-foto mereka di media sosial. Tampak jelas ada kebahagiaan dalam relasi yang sedang mereka jalani. Ditambah lagi, bagi para perempuan, rasanya aman dan nyaman saat bisa mendongakkan kepala ke arah pasangan yang juga tersenyum padanya.
“Aku pengen kayak mereka,” pikirku. “Tapi aku juga pengen pacaran sekali seumur hidup… kayak Papa sama Mama.”
Singkat cerita, akhirnya aku bertemu dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan kriteriaku. Cinta Tuhan, aktivis gereja, punya hati bagi kaum muda (seperti passion-ku), bisa main musik, cerdas, dan cukup mapan secara finansial. Tapi yang membuatku tertarik padanya adalah bagaimana dia memperlakukanku: sangat memaklumi kelabilanku, selalu ada di titik terendah hidupku, bahkan dia duluan yang menyatakan ketertarikannya padaku. Siapa coba yang tidak tertarik pada cowok seperti itu?
Masalahnya adalah pada penampilan fisiknya.
Bukannya secara wajah dia tidak tampan, tapi dia mengidap penyakit yang mengubah bentuk fisiknya. Padahal dari dulu, aku juga ingin memiliki pasangan yang sehat dan lebih tinggi dariku. Secara kasarnya, “Kalau orang yang tidak lebih rohani dariku bisa punya pasangan yang sehat dan sempurna, kenapa aku harus berjalan bersama laki-laki seperti ini?”
Ya, kalimat itu menggambarkan kesombongan rohani yang selama ini kupendam.
Sejak berelasi dengan laki-laki ini, memang sih, aku ‘merasa’ jadi lebih dekat dengan Tuhan, tapi itu karena aku mengeluh tentang kondisinya yang tidak bisa kuubah. Entah berapa liter air mata yang terkuras untuk mendoakan sesuatu yang mustahil terjadi dan entah berapa kali aku ingin mundur tapi dia justru mencengkeramku, “Nggak. Kita nggak boleh mundur!” Tapi lagi dan lagi, relasi kami bisa kembali pulih (meskipun kami sempat hampir putus saking putus asanya).
Kukira semua permasalahan di atas hanyalah cobaan dari si jahat agar relasi ‘yang diberkati’ ini bisa berakhir. Apalagi melihat dukungan dari banyak orang yang terus mengalir. Aku semakin memendam harapanku untuk menjalin relasi dengan orang yang benar-benar sesuai dengan kriteriaku dan bersikap baik-baik saja terhadap relasi kami.
Tanpa kusadari, ternyata semua itu hanyalah kebahagiaan yang semu.
Aku hanya mencari sosok yang sanggup melimpahiku dengan perhatian dan kasih sayang, sehingga (dengan lugunya) membiarkan ada—setidaknya—dua kejadian ini:
Waktu Belum Jadian
Dulu aku merasa bahwa pergi berdua (alias nge-date) hanya boleh dilakukan setelah pacaran. Setidaknya ada ‘payung’ yang mengesahkan status kami agar tidak jadi bahan gosip orang lain, ya nggak? Buatku yang strict saat itu, kalau belum ada kejelasan status, ngapain pergi berdua?
Tiba-tiba suatu hari, dia ingin agar kami bisa merayakan hari ulang tahunnya berdua.
Aku berusaha menolaknya, tapi dia berkata dengan memelas, “Apa nggak boleh kalau aku pengen ngerayain ulang tahunku berdua sama kamu?”
Meskipun pada akhirnya kami pergi berdua untuk sarapan, hatiku merasa tidak damai—apalagi saat bertemu dengan salah satu keluarga jemaat dari gereja kami. Aku merasa tidak damai sejahtera karena hal yang kami lakukan ini.

Setelah Jadian
“Kardigannya dilepas, dong.”
Aku menatapnya dengan bingung. Padahal dia tahu kalau aku tidak suka pakai baju berlengan buntung, makanya aku pakai kardigan. “Tapi dingin…” kataku.
Setelah membujukku beberapa kali, akhirnya aku luluh. Dengan polosnya, aku membiarkan tubuhku bersandar pada dirinya, sementara tangannya mengusap-usap lenganku. Tiba-tiba aku mendengarnya memanggilku dengan bisikan lembut sambil memegang bahuku. Siapa yang tidak ingin melayang kalau sudah diperlakukan demikian?
Jangankan bercerita pada keluarga, untuk bisa saling menyentuh pun kami harus sembunyi-sembunyi. Rasanya malu kalau sesama aktivis gereja—dan dikenal bertumbuh serta pasangan yang punya “relationship goals”—ini juga melakukan hal-hal seperti di atas?
Kemudian aku merenungkan hal ini:
Apakah aku terlalu polos, sampai tidak berani untuk membangun batasan tegas terhadapnya? Atau aku hanya takut kehilangan sumber kasih sayang dan perhatianku? Kalau kami memang saling menyayangi, mengapa aku merasa hubungan ini jadi seperti sebuah transaksi?
“Nggak apa-apa lho, Dek, kalau kamu mengakui kamu tidak kuat buat menjalin relasi ini.”
“Aku masih kuat kok, Kak,” bantahku. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada air mata di pelupuk mataku.
“Iya, it’s okay,” balas sang Kakak dengan lembut. “Tapi kalau boleh saran, coba kamu pikirin bener-bener, ya.”

Aku benci mengakuinya, tapi sejak percakapan random di perpustakaan kampus itu, pemikiranku terhadap relasiku selama ini benar-benar berubah.
Mungkin ada orang yang seperti Kanae Miyahara yang bisa menerima Nick Vujicic, tapi itu bukan aku. Salahkah jika pada akhirnya aku melambaikan bendera putih dan menyatakan pada orang-orang bahwa aku tidak sanggup mencintai pasanganku sejauh itu?
Setelah melalui berbagai pertimbangan, aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Selain karena ketidaksanggupanku untuk mencintai dan menerimanya apa adanya, aku juga belum siap untuk masuk ke jenjang yang lebih serius dalam waktu dekat (katakanlah setahun atau dua tahun lagi).
Ini kesekian kalinya aku mengatakan bahwa aku ingin putus. Biasanya kalau sudah putus asa (terhadap apapun, apalagi dengan kondisi relasi kami), aku bisa tiba-tiba bilang, “Aku mau putus. Soalnya gini gini…” Kalau sudah begitu, dia tahu itu artinya kalau aku sudah capek—jadi dia menyuruhku untuk beristirahat. Tapi kali ini berbeda.
Meskipun dia bisa menerimaku apa adanya, tapi bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Tidakkah kedua pihak justru jadi terbebani? Bukankah cinta seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilalui bersama, walaupun kadang-kadang ada pahit di dalamnya?
Singkat Cerita, Kami Putus
Buatku pribadi, sebagai perempuan yang mendambakan, “hanya berpacaran sekali seumur hidup”, ini mimpi buruk. Belum cukup di situ, sampai sekarang aku masih teringat kata-kata mantan pacarku itu sebelum kami putus:
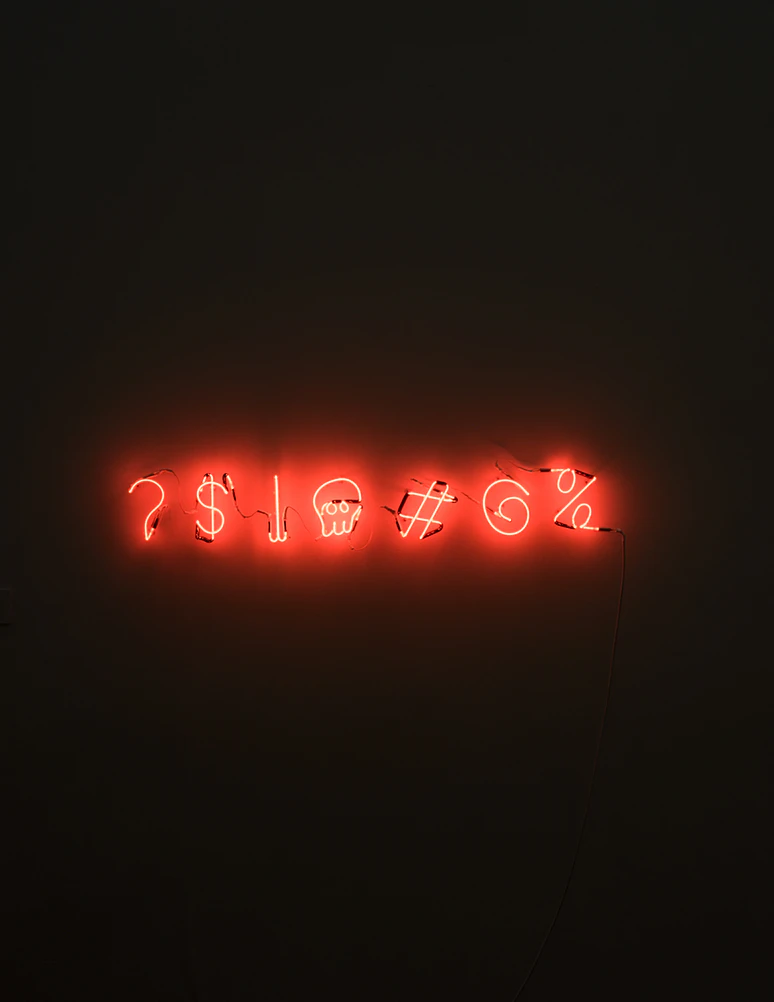
1. “Apa kamu kayak gini karena kamu ke-trigger? Mungkin dari kuliah, atau obrolan sama temen-temenmu…”
Iya, mungkin dari dulu dia berpikir bahwa aku tipe orang yang mudah ikut-ikutan omongan orang lain. Padahal bukankah hal yang wajar ya, kalau dari situ kita menyadari bahwa memang ada yang harus dibereskan?
2. “Ya nggak apa-apa kalau kamu mau putus. Berarti pilihanmu cuma dua: Mau cari pangeran yang sempurna kayak di dunia dongeng—yang bisa memenuhi semua impianmu, atau kamu mau jadi single seumur hidup karena kamu nggak nemuin yang sesuai kayak kriteriamu. Padahal untuk sekarang aja udah ada aku yang bisa menerima semua kekuranganmu. Tapi kamu nggak bisa menerima kekuranganku.”
“Sorry to say,” kata temanku yang lain setelah aku menceritakan perkataan sang mantan, “tapi itu manipulatif banget, lho.” Setelah temanku berkata demikian, aku jadi bertanya pada diriku sendiri, “Apakah tindakan mengekang (menurutku) seperti ini masih bisa disebut cinta?”
Saat kami benar-benar sudah putus, aku berusaha untuk tidak mencari tahu kabar tentang dirinya. Kadang-kadang saat swipe story, aku tidak sengaja melihat update status-nya. Yah, setidaknya saat ini dia sudah bisa mulai bangkit lagi, seperti diriku. Tapi tetap saja, sulit rasanya untuk menahan diri agar tidak menimbulkan perhatian yang bisa memicu prahara baru. Hah.
***
Di momen terkelam inilah, tanpa diduga, ada dosen yang berkata di kelas, “Kalau kehadiran pacarmu itu menggantikan posisi Allah, Allah bakal mengorkestrasi, bagaimanapun caranya, untuk membawamu kembali pada-Nya.”
“… bahkan kalaupun harus sampai putus,” batinku.
Entah kenapa, setelah membatin begitu, aku merasa ada damai sejahtera di hatiku. Perasaan itu bukan berarti menandakan hubungan kami yang sudah terjalin lebih dari tiga tahun ini sia-sia. Tidak. Selama berpacaran dengannya, aku belajar sangat banyak—baik darinya maupun berbagai pelajaran yang Tuhan berikan pada kami. Namun saat kami harus berpisah, aku juga merasa lega karena telah menyuarakan ganjalan yang kupendam selama ini. Meskipun kadang-kadang masih ada perasaan bersalah yang mampir di pikiranku, aku bersyukur karena (lagi-lagi), Tuhan hadir melalui banyak cara yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya.
Berkaca dari pengalaman ini, aku belajar bahwa sebelum menjalin relasi dengan seseorang, aku benar-benar harus merasa puas sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan John Piper, “God is the most satisfied when we are most satisfied in Him.” Bagaimana mungkin Tuhan dimuliakan jika aku masih ingin mengubah (calon) pasanganku, sementara aku juga masih memiliki banyak hal untuk dibenahi?

Cukup sekali saja pengalaman pahit ini harus kutelan. Aku tidak mau berjalan berdasarkan pemikiranku sendiri, melainkan benar-benar berserah kepada Tuhan, Sumber Hikmat itu. Tidak mudah, memang. Apalagi aku tipe orang yang perfeksionis dan cukup terencana. Namun jika penyerahan diri total ini membuatku semakin mengenal Tuhan, aku mau taat dan percaya kepada-Nya.
Untuk menjadi bagian dari gerakan generasi
muda Kristen Indonesia. Kirimkan karyamu ke: